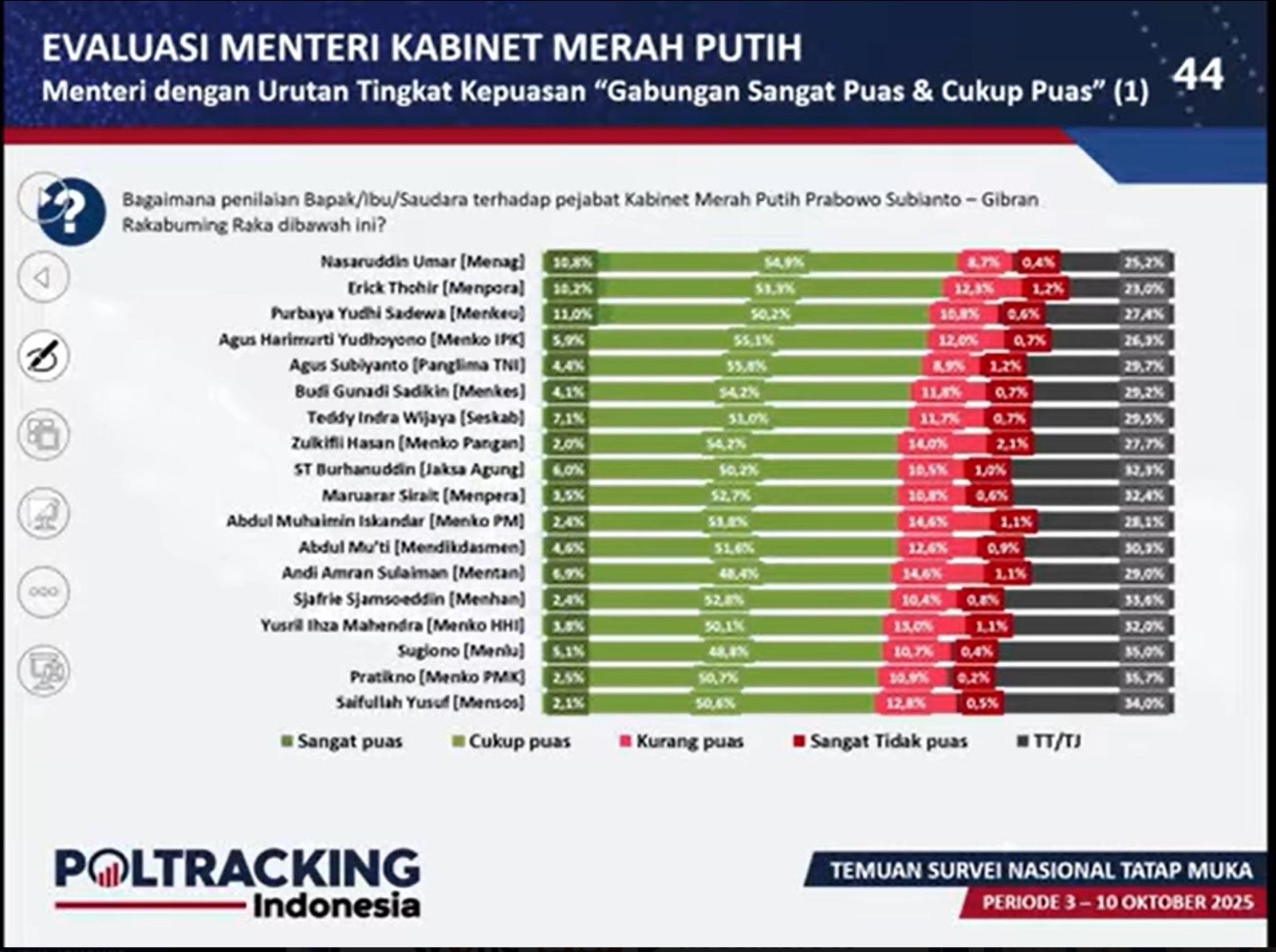Relasi Agama Dan Negara Dalam Spirit Proklamasi Kemerdekaan
Kontributor

Oleh: Saddam Husain, Pondok Pesantren As’adiyah
Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan keputusan menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Melihat kondisi tersebut, kelompok pemuda mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno menolak.
Para pemuda terus mendesak hingga akhirnya berakhir dengan peristiwa penculikan Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945.
Saat ditanya oleh Sukarni, salah satu pemuda yang menculik Soekarno, “Mengapa justru diambil tanggal 17, mengapa tidak sekarang saja, atau tanggal 16?”
Lalu Soekarno menjawab, “Saya merasakan di dalam kalbuku, bahwa tanggal 17 adalah saat yang baik, angka 17 adalah angka suci. Tanggal 17 itu hari Jumat, Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Qur’an diturunkan tanggal 17, orang Islam sembahyang 17 rakaat, oleh karena itu kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia.”
Demikianlah alasan Soekarno yang bersifat simbolis-religius sekaligus kultural.
Sejarah ini memperjelas bahwa agama dan negara tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi. Agama memberi legitimasi spiritual, arah moral, dan rasa syukur, sementara negara menjadi wadah untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa.
Dalam konteks Indonesia, agama dan negara tidak menyatu secara total (integralistik), tetapi juga tidak dipisahkan sepenuhnya (sekularistik). Keduanya memiliki relasi yang bersifat simbiotik.
Indonesia bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler. Namun, agama dan negara saling membutuhkan, memberi makna, dan menopang, tanpa saling menegasikan.
Dengan demikian, Proklamasi 17 Agustus dapat dimaknai sebagai momentum spiritual yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.